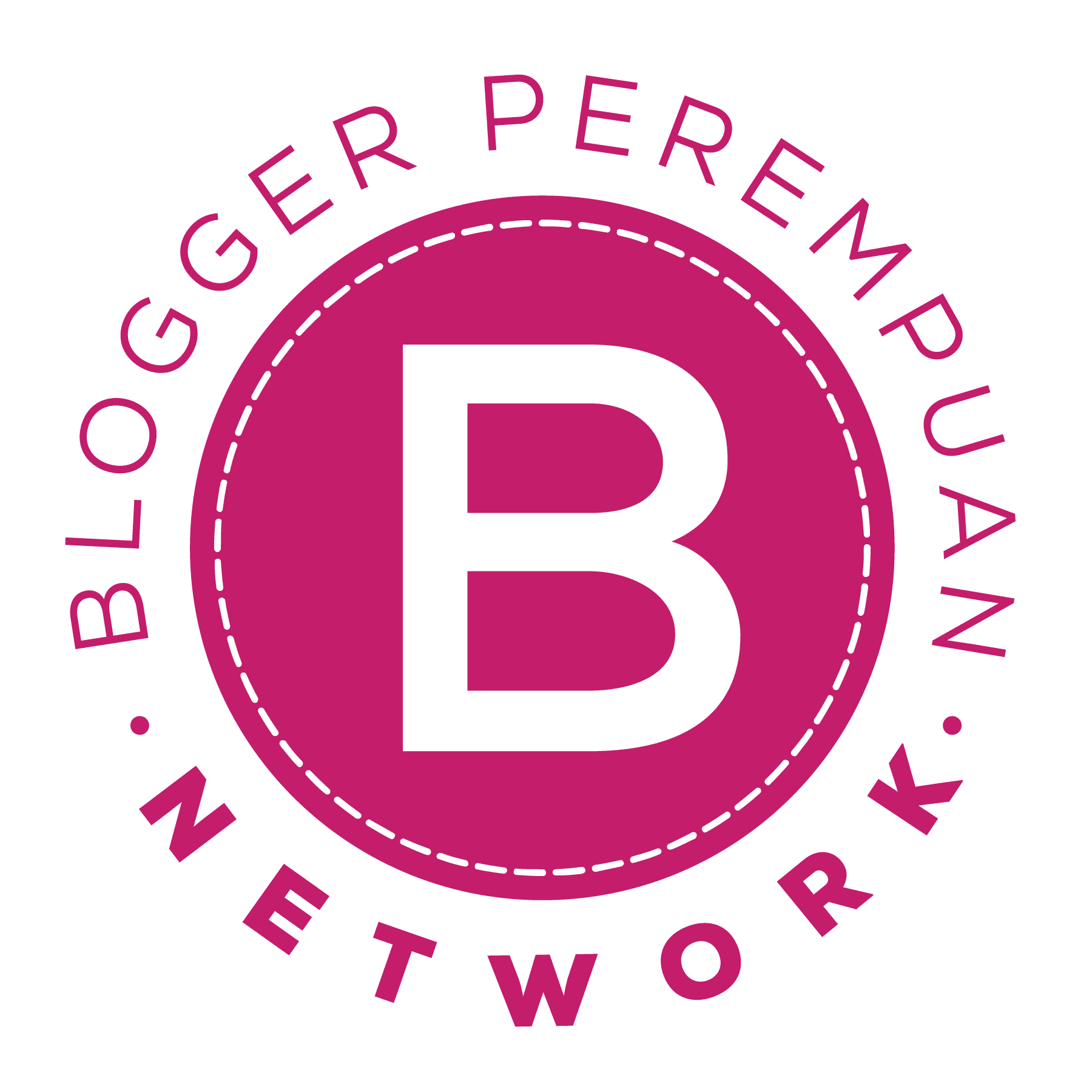“Menikah itu susah. Sorooo….”ibuku sering mengulang-ngulang hal ini. Beliau ingin sekali meyakinkanku bahwa menikah itu sangat susah. Sulit banget. Nggak ada indah-indahnya. Entah apa tujuan ibu terus menerus membombardirku dengan kalimat ini setiap kali aku pulang ke rumah di masa liburan kuliah.
Ibu adalah politikus handal dalam keluarga kami. Tak ada satu pun gerak-gerik ibu atau perkataan ibu yang tidak ada maksud di belakangnya. Termasuk doktrinasi bahwa menikah itu susah yang diberikannya padaku, pasti dan pasti karena beliau tidak ingin aku buru-buru menikah. Aku harus berkarir super sukses dulu sebelum akhirnya duduk di pelaminan. Dan aku sangat mengamini hal itu.
Tidak pernah terbesit sekalipun juga di dalam benakku di masa remaja atau bahkan masuk usia SMA bahwa aku akan menikah secepatnya. Aku ingin berkarir dulu, jelas. Menikah adalah urutan kesekian.
Mestinya begitu. Rencananya begitu. Akan tetapi Allah SWT tidak menganggap rencanaku itu baik karena Maha Mengetahui yang lebih baik dan terbaik untuk kehidupanku.
Anak gadis yang ambisius untuk menjadi wanita karir ini, malah ketemu seorang laki-laki di semester pertama kuliahnya. Dan tanpa ada settingan sama sekali, akhirnya berjodoh menikah dengannya tepat 3 bulan sebelum lulus kuliah.
Doktrinasi ibu tidak mempan padaku saat itu. Menjalani kehidupan yang sulit dan susah bukan hal yang mengerikan bagiku. Aku pernah makan nasi yang aku masak dari beras yang sudah kupisahkan dari tahi tikus yang masuk ke lemari dapur tempat kos kami di Bandung. Aku kuliah dari pagi sampai sore dengan bekal makan supermie dan kocokan nutrisari sebotol. Aku begadang sampai pagi menyelesaikan semua tugas kuliah dengan camilan campuran gula dan kopi bubuk instan yang aku anggap sebagai pengganti permen Nescafe.
Bahkan aku sering sengaja main ke rumah teman asli Bandung di waktu makan siang dan makan malam, karena uang kirimanku sudah habis sebelum akhir bulan. Ini biasa terjadi ketika masa fotokopi tugas-tugas semakin banyak dan menyedot uang jatah bulananku sebesar 150ribu rupiah sebulan itu.
Aku tak takut miskin, karena dari kecil ibu membiasakan kami makan dengan lauk seiris tempe tipis dan sesendok indomie yang sudah dicampur potongan cabe rawit dan kecap. Lauk yang harus cukup dimakan 10 orang di rumah kami.
Jadi susah karena menikah tidak mengerikan. Yang menakutkan adalah aku berhenti karena menikah. Aku menjadi titik. Aku menjadi ibu rumah tangga. Itu terlalu menakutkan untuk dibayangkan. Karena ibu seringkali menakutiku bahwa jika perempuan tidak bekerja itu rentan untuk diperlakukan secara sembrono oleh suaminya.
Semakin kamu anti terhadap sesuatu biasanya Tuhan akan mencobamu dengan hal itu. Ketika aku anti banget menjadi ibu rumah tangga. Maka Tuhan menggerakkan telapak tangannya. Dan dengan sekejap saja tangan itu dibalik. Dan posisiku menjadi calon peneliti dengan karir cemerlang langsung berubah total menjadi ibu muda yang sedang hamil dan tidak berdaya.
Aku dan suamiku turun dari angkot berwarna coklat yang mengantarkan kami dari stasiun Gubeng ke pinggir jalan. Rumah ibuku masih berjarak sekitar 300 meter lagi. Kami berjalan kaki dengan masing-masing tangan membawa tas besar berisi baju, buku dan beberapa barang kami dari tempat kos di Bandung.
Sepeda, magic com dan barang yang besar, kami titipkan ke temannya suamiku yang masih ada di Bandung. Rencananya jika dia juga akan pindah kembali ke Surabaya, barangku akan dibawa serta dan dikirimkan ke rumahku.
Tanpa riuh rendah penyambutan, aku dan suamiku membuka pintu pagar ibuku secara perlahan. “Loh sudah datang?” ibu dan bapakku kaget melihat kami sudah masuk ke rumah. Sementara baru beberapa hari lalu, kami menelepon mereka dan mengabarkan bahwa aku sedang hamil.
“Kamarmu belum dibersihkan e Hen,”kata ibu.
Aku bergegas memasukkan barang bawaanku ke kamar dan berkata pelan,”nggak papa bu, nanti kami bersihkan sendiri.”
Aku lihat kasur yang tidak ada spreinya. Dan kamar terasa sedikit berdebu. Kamar ini dibiarkan kosong ketika kami berangkat ke Bandung, tiga bulan setelah menikah. Tanpa beristirahat, aku dan suami segera membersihkan kamar dan membersihkan diri. Kami ingin beristirahat setelah naik kereta api dari Bandung ke Surabaya selama 12 jam lebih.
Selesai membersihkan diri, aku berdiam di dalam kamar. Berat sekali rasanya perasaan ini. Kembali pulang tanpa sempat menjadi apa-apa. Padahal baru kemarin bapak menyorotkan binar mata bahagia ketika mendengar aku diterima kerja langsung di LIPI. Dan suamiku bisa tetap kerja lagi di IPTN setelah dia lulus kuliah lanjutan di ITS nanti. Dua pegawai BUMN yang sudah menentramkan hati orang tuanya ini, sekarang malah kembali ke rumah tanpa membawa kabar apa-apa selain kembali pulang karena hamil muda.