Suamiku mengambil cuti belajar untuk kuliah lagi ke ITS. Dia dulu lulusan D3 Teknik Mesin (D3MITS), kemudian langsung bekerja di IPTN (INDUSTRI PESAWAT TERBANG NASIONAL), perusahaannya pak B.J. Habibie yang bikin pesawat terbang dan terakhir berubah nama menjadi PT. Dirgantara Indonesia.
Beberapa bulan setelah kami dekat dan niat serius menjalani hubungan, dia memutuskan untuk melanjutkan kuliah lagi, sehingga bisa lulus S1 di jurusan yang sama juga, Teknik Mesin ITS. Jadi sebelum menikah, kami menjalani LDR juga Long Distance Relationship Surabaya-Bandung, kurang lebih 4 tahun.
Sebenarnya jika semua rencana kami terlaksana dengan detil, suamiku ini lulus barengan dengan aku. Jadi, wajar jika kami berani saja mengiyakan ketika keluarga memutuskan tanggal baik pernikahan kami adalah sebelum aku lulus kuliah. Prediksi kami saat itu, 3 bulan setelah menikah, aku lulus, kemudian suamiku juga lulus. Kami berdua jadi sarjana lalu kembali ke Bandung. Aku bekerja jadi peneliti di LIPI Bandung. Dia kembali ke kantornya di IPTN. Menjadi duo pasangan pegawai BUMN. Sempurna.
Hamil dan memiliki anak, bukan hal yang kami bahas detil saat itu. Kami adalah Discussion Couple. Sejak awal kami suka membicarakan banyak hal secara serius. Tapi sepertinya, bagi anak muda Jawa, membicarakan tentang rencana mempunyai anak, yang alhasil akan nyerempet ke hal yang tabu, itu masih bikin sungkan untuk dibicarakan.
Kami tidak memprediksikan hal ini. Tidak juga menggunakan kontrasepsi untuk menunda kehamilan. Atau bahkan kami tidak sempat memikirkan hal itu juga. Bayangkan saja selama proses menjelang menikah, aku harus masih berkutat di laboratorium penelitian juga mempersiapkan bahan untuk seminar Tugas Akhir dan sidang sarjana.
Dan rupanya kehidupan sedang bercanda pada kami berdua. Tepat beberapa hari setelah kami pindah ke tempat kos yang lebih baik, lebih bersih dan jauh lebih dekat dengan LIPI tempatku bekerja, aku hamil.
Aku pikir telat datang bulan kala itu biasa saja karena kecapekan pindahan kos. Aku mengangkat koper, lemari, kasur dan segala perangkat dari Surabaya ke Bandung juga dari kos lama ke kos baru. Dengan menjadi tukang angkut barang berat saat itu, menurutku mustahil seorang perempuan bisa hamil gitu loh. Ibarat kata, kalau toh beneran jadi, bisa-bisa ambrol tuh calon jabang bayi.
Tapi rupanya anakku nih setrongnya luar biasa. Atau rahimku yang tebal dan kuat. Belum hilang rasa capek kami karena pindahan, ternyata rasa mual dan tidak enak badan setiap hari yang kualami adalah tanda-tanda kehamilan.
----------
“Mas, sini sini.” Aku memanggil suamiku yang berkutat di depan computer setelah sholat shubuh.
Aku menyorongkan cawan petri berisi urin pertama pagi. Lalu membuka kemasan bertuliskan ONE MED yang aku beli di apotek kemarin sepulang dari LIPI. Aku baca sekilas petunjuk pemakaiannya lalu memasukkan batang berisi petunjuk kehamilan itu ke dalam urin yang sudah aku kumpulkan sebelum shubuh tadi.
Aku tidak sedang mengharapkan hamil. Ini sudah percobaan test pack ke sekian kalinya sejak kami awal menikah. Dan hasilnya selalu negative. Aku pikir saat itu pun akan sama. Aku memanggilnya untuk menyaksikan pertunjukan sulap saja atau main tebak-tebakan setelah aku sudah telat datang bulan sekitar satu minggu lebih.
“hayoo berapa garis jadinya, eng ing eng…”candaku.
Sruuttt…..tak sampai satu detik, langsung terpampang nyata ada DUA GARIS di test pack yang aku pegang itu. Jantungku rasanya melorot langsung ke dengkul.
“ha….dua gariiiss..???”desisku perlahan.
Sebaliknya, “Alhamdulillah dua garis!”suamiku bertepuk tangan spontan.
------
Dua garis itu membuatku lemas. Tak tahu harus berekspresi apa. Dan aku merasa bersalah juga tidak langsung berteriak hore atau Alhamdulillah atau super senang akan kehamilan ini seperti halnya momen yang muncul di iklan televise.
Pas setelah ada dua garis melintasi test pack di subuh pagi itu, aku sudah yakin bahwa kembali ke Surabaya adalah jalan yang akan kami pilih.
“Kamu masih mau tetap kerja di LIPI?” dia bertanya dengan hati-hati setelah kondisi tenang siang hari.
Aku sudah tahu arah pembicaraan ini.
“Iya, kalau bisa,”jawabku tak kalah perlahannya.
“Apa bisa kamu hamil sendirian di sini? Kerja juga? Dari kemarin aja lemes banget. Nanti yang belikan makanan siapa? Yang ngantar kerja siapa?”
Aku terdiam. Pikiranku berputar. Memikirkan hal ini sendiri. Jadi anak perempuan yang masih muda, sudah menikah, lalu hamil dan merantau tanpa satu pun sanak family, bikin aku ketakutan juga. Apalagi suamiku. Dia benar-benar tidak mau meninggalkan aku sendirian di Bandung.
Suamiku bukan tipe orang yang memberikan keputusan secara saklek. Kami sudah dekat selama 4 tahun sebelum akhirnya diijinkan untuk menikah. Sedikit banyak dia tahu karakterku yang susah dilarang jika sudah ada kemauan. Dan menjadi peneliti, bekerja di LIPI, jelas dia tahu itu adalah impianku. Impian terbesarku. Puncak target hidupku.
Sejak percakapan itu aku terus menimbang-nimbang. Membayangkan ini itu. Bagaimana jika ini. Bagaimana jika itu. Apakah aku sanggup jika begini. Apa yang mungkin terjadi jika begitu.
Hal yang paling membuatku takut adalah karena aku bekerja di laborarium biokimia. Selama menjalankan penelitian tugas akhir, ada beberapa reagen kimia yang karsinogenik (bisa memicu kanker).
“Kalau aku ngotot kerja di LIPI. Dalam keadaan lemah, capek, sendirian, apakah aku kuat? Bagaimana jika aku terpapar reagen karsinogenik? Bagaimana jika nanti zat itu terkena janinku? Jangan-jangan nanti dia cacat. Kalau iya, nanti anakku jadi susah. Aku pun jadi susah.”
“Tapi, kalau aku berhenti, impianku akan musnah. Mana yang harus kupilih, anakku atau impianku?. Sepertinya tidak ada masalah aku tetap bekerja, toh ibu itu, ibu itu yang bekerja di LIPI, anaknya sehat-sehat saja.”
“Ah, Tapi mereka orang asli Bandung.”
“Kalau aku di sini, suamiku nanti bagaimana? Nanti dia kepikiran. Semakin kepikiran aku di sini, semakin dia nggak bisa fokus menyelesaikan skripsinya. Nanti dia nggak lulus-lulus. Bisa kena pinalti dari kantor. Kalau akhirnya di PHK gimana?”
Ini semua adalah kata-kata yang terdengar di dalam batinku sendiri. Sampai akhirnya aku merasa bahwa harus ada salah satu yang berkorban di sini. Yang pasti bukan suamiku yang berkorban karena dia adalah kepala keluarga. Tentu juga bukan anakku yang dikorbankan, karena dia tidak minta dihadirkan ke rahimku.
Jadi, tidak ada pilihan lagi, harus aku yang mengorbankan diri. Menikah adalah keputusanku. Memastikan kehamilanku terjaga sampai anakku lahir adalah tanggung jawabku. Tanpa ragu lagi, aku katakan pada suamiku pada malam itu,”biar aku rapikan barang-barang. Packing. Kita kembali saja ke Surabaya.”





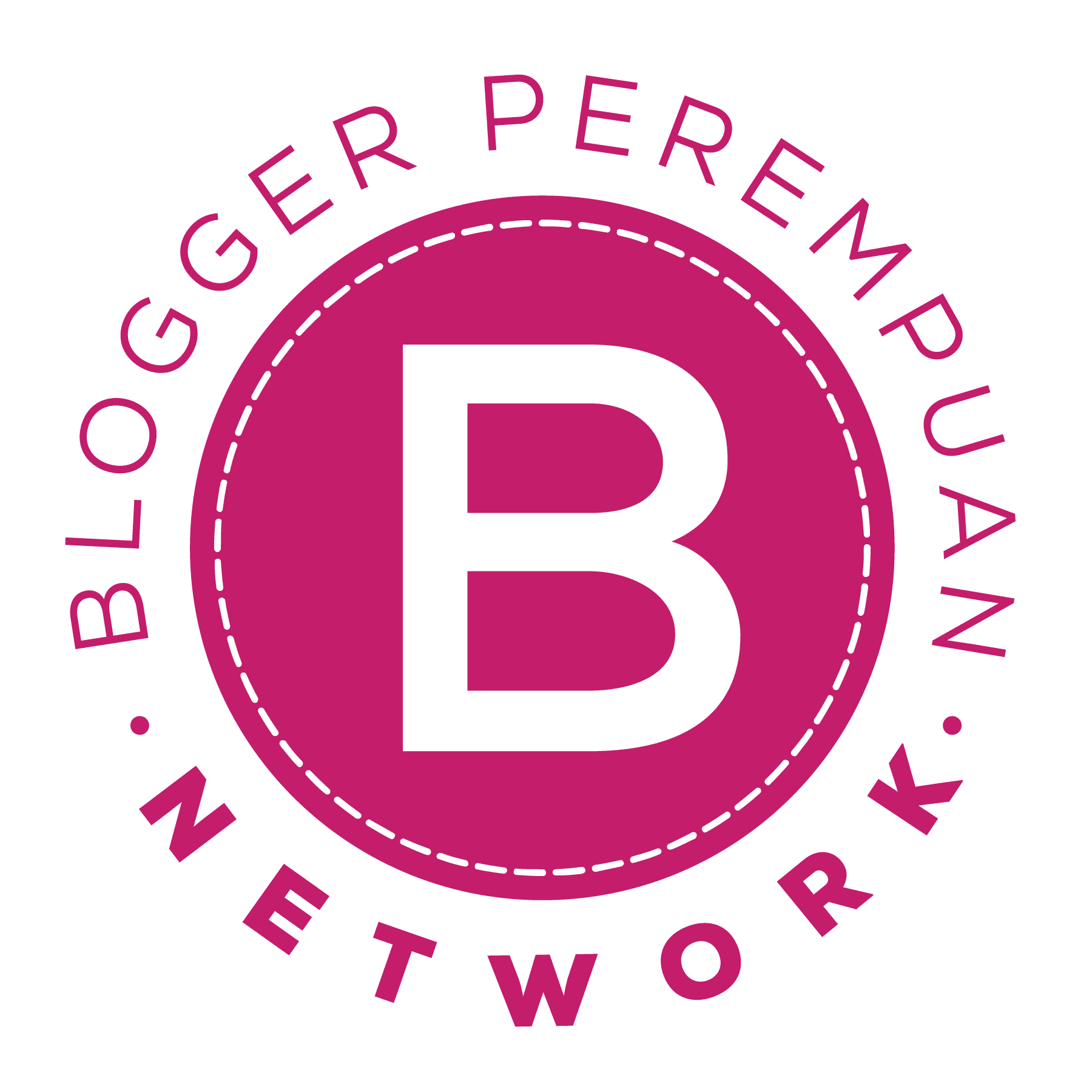








Tidak ada komentar
Thanks For Your Comment :)